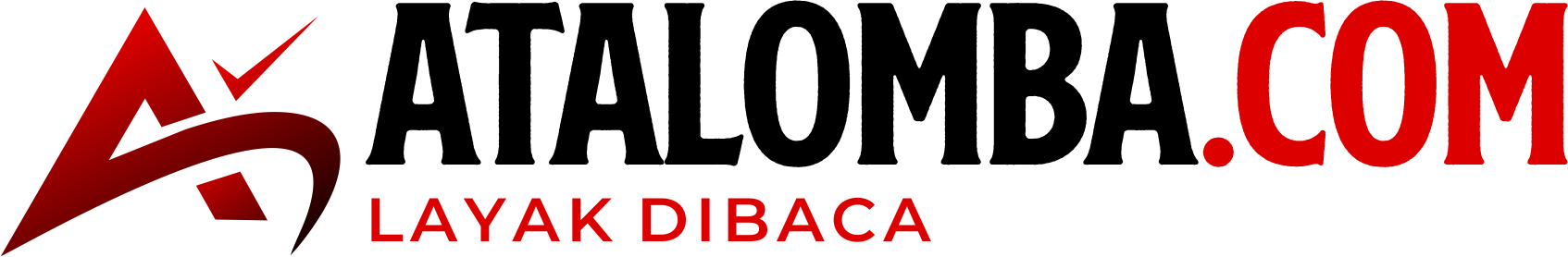Bung Karno, Gereja, dan Kontemplasi yang Melahirkan Pancasila

Oleh: Irminus Deni
Selama hampir empat tahun di Ende (1934–1938), Bung Karno hidup dalam keterbatasan fisik, tapi dalam keluasan batin. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana, tak jauh dari Gereja Katedral Ende. Setiap pagi, suara lonceng Gereja membangunkannya. Ia berjalan kaki, mengajar anak-anak, bermain drama, menulis naskah-naskah panggung, dan duduk merenung di bawah pohon sukun yang kini dikenang sebagai “Taman Renungan Pancasila”.
Namun, yang tidak banyak diketahui, adalah bagaimana Bung Karno menjalin hubungan yang sangat baik dengan para imam Katolik dari Serikat Sabda Allah (SVD) yang telah lama menetap dan bekerja di Ende. Para misionaris itu adalah Pater Gerardus Huijtink SVD dan Pater Johannes Bouma SVD. Mereka adalah misionaris asal Belanda yang tinggal di Biara SVD St. Yosef Ende. tidak hanya berkarya sebagai rohaniwan, tetapi juga sebagai pendidik, pustakawan, dan pelayan masyarakat. Dalam interaksinya dengan mereka, Bung Karno menemukan ruang diskusi yang jujur, terbuka, dan egaliter.
Dari perpustakaan milik SVD, Bung Karno membaca karya-karya filsuf Eropa, sejarah revolusi dunia, dan pemikiran sosial-politik modern. Ia juga berdiskusi tentang nilai-nilai universal yang melintasi batas agama, keadilan sosial, martabat manusia, kasih, dan kebebasan. Meski seorang Muslim, Bung Karno tak pernah menutup diri dari percakapan lintas iman. Ia terbuka, belajar, dan menimbang-nimbang nilai-nilai itu dalam terang perjuangan bangsanya.
Dalam kesaksiannya, Bung Karno menyebut masa di Ende sebagai masa sunyi yang subur. Di sana ia tidak bisa berorasi atau memimpin massa, tapi ia bisa berpikir. Ia bisa menggali nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi jiwa bangsa. Ia merenung bukan dalam kemarahan, melainkan dalam kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman spiritual dan sosial yang dalam.
Gereja Sebagai Ruang Intelektual dan Dialog
Gereja Katolik di Ende pada masa itu telah menjadi pusat peradaban. Di tengah keterbelakangan ekonomi dan akses pendidikan yang terbatas, Gereja hadir dengan semangat pelayanan. Sekolah-sekolah didirikan, rumah sakit dibuka, kursus keterampilan digelar. Para pastor dan bruder bekerja dengan semangat inkulturatif, mereka mempelajari bahasa lokal, hidup sederhana bersama umat, dan menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas.
Bung Karno menyaksikan semua itu. Ia melihat bahwa agama tidak hanya hadir di mimbar dan doa, tetapi juga dalam kerja nyata untuk kemanusiaan. Ia menyaksikan bagaimana Gereja bisa menjadi agen perubahan sosial yang efektif, bukan lewat kekuasaan, tapi lewat pelayanan. Pengalaman ini membentuk cara pandang Bung Karno terhadap peran agama dalam kehidupan publik. Ia menyadari bahwa Indonesia yang hendak dibangun harus membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap agama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Inilah yang kelak menjadi cikal bakal dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang memaksakan satu tafsir agama, tapi ketuhanan yang membuka ruang bagi perjumpaan nilai-nilai transenden yang hidup dalam berbagai iman dan budaya. Di Ende, Bung Karno belajar bahwa iman tidak harus menjadi tembok, tapi bisa menjadi jembatan. Gereja, dalam konteks itu, menjadi ruang ketiga, antara politik dan rakyat, antara spiritualitas dan kebangsaan.
Di Bawah Pohon Sukun, Merenungkan Indonesia
Taman Renungan Pancasila bukan sekadar situs wisata sejarah. Ia adalah simbol paling otentik dari sebuah proses intelektual dan spiritual yang mendalam. Di bawah pohon sukun itu, Bung Karno duduk dan merenung. Ia menimbang nasib bangsanya yang terjajah. Ia membayangkan Indonesia sebagai rumah besar bagi semua, bukan hanya bagi satu golongan, satu suku, atau satu agama.
Dalam kesunyian itulah Bung Karno mulai menyusun kerangka ideologis yang kemudian menjadi Pancasila. Ia tidak menciptakannya secara tiba-tiba dalam sidang BPUPKI tahun 1945, tetapi sudah mulai memikirkannya sejak di Ende. Nilai-nilai yang ia rumuskan berasal dari pengalaman hidup bersama masyarakat, dari perenungan mendalam, dan dari dialog-dialog lintas iman yang memperkaya jiwanya.
Pancasila, dalam pengertian ini, adalah hasil dari sebuah perjalanan batin. Ia bukan produk akademis belaka, tetapi hasil dari pengalaman konkret yang dihayati Bung Karno selama masa pengasingan. Dan dalam pengalaman itu, Gereja dan masyarakat Ende memberikan sumbangan yang tidak bisa diabaikan.
Relevansi Kini, Belajar dari Ende
Dalam situasi bangsa hari ini, di mana narasi identitas sering kali dijadikan alat politik, kisah Bung Karno di Ende menjadi sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa kebesaran sebuah bangsa tidak lahir dari dominasi satu kelompok atas yang lain, tetapi dari dialog, keterbukaan, dan pengakuan atas kemajemukan. Indonesia lahir dari keberanian untuk merangkul perbedaan, sebuah semangat yang ditumbuhkan secara organik di tempat-tempat seperti Ende.
Kita perlu menghidupkan kembali semangat itu, bahwa agama dan negara tidak perlu dipertentangkan, bahwa iman dan nasionalisme bisa berjalan berdampingan, dan bahwa Gereja, masjid, pura, dan vihara bisa menjadi ruang bersama dalam membangun keadaban publik. Bung Karno sudah memberi contoh, ia tidak pernah kehilangan keyakinannya sebagai Muslim, tetapi ia juga tidak pernah menolak pelajaran-pelajaran luhur dari Gereja dan iman Katolik.
Ende sebagai Rahim Sejarah
Sejarah Indonesia tidak hanya ditulis di Jakarta atau Yogyakarta. Ia juga ditulis dalam sunyi oleh kota-kota kecil yang sering kali diabaikan, seperti Ende. Di sana, dalam pengasingan, Bung Karno tidak sekadar menunggu waktu. Ia membangun gagasan, menulis sejarah, dan menyusun kerangka ideologis untuk bangsa yang belum lahir.
Gereja Katolik, dalam segala kesederhanaan dan kesetiaannya pada pelayanan, menjadi bagian dari proses itu. Ia tidak menuntut pengakuan, tetapi warisannya hidup dalam ideologi yang mempersatukan kita hari ini.
Dari Ende, kita belajar bahwa bangsa besar tidak lahir dari ego, tapi dari perenungan yang jujur. Tidak lahir dari kebencian, tapi dari kasih dan Persaudaraan. Dan tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari keberanian untuk merenung, menerima, dan menyatukan.*Penulis adalah Alumni Universitas Bung Karno Jakarta.