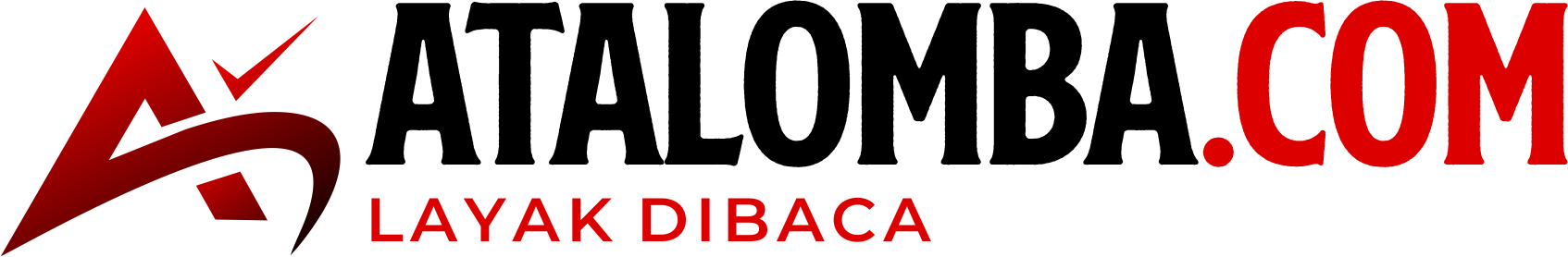Telinga Panas, Bangsa Dewasa

Ada reaksi psikologis yang sangat umum terjadi setiap kali kritik disampaikan di ruang publik kita, telinga memanas, wajah memerah, emosi naik ke kepala. Seolah-olah kritik bukan sekadar pendapat yang berbeda, melainkan sebuah serangan pribadi yang harus segera dilawan atau disangkal.
Fenomena ini tampaknya sederhana. Namun jika ditelusuri lebih dalam, respons semacam ini menyimpan persoalan besar, kurangnya kedewasaan dalam bernegara dan bermasyarakat. Bung Hatta, salah satu Bapak Pendiri bangsa ini, pernah memperingatkan: “Demokrasi tanpa kritik adalah demokrasi yang mati.”
Namun kini, kita menyaksikan demokrasi yang justru alergi terhadap kritik. Suara-suara yang mengingatkan dianggap sebagai gangguan, mereka yang bertanya diperlakukan sebagai musuh. Seringkali, kritik dipelintir menjadi bentuk “pencemaran nama baik,” “perbuatan tidak menyenangkan,” atau ancaman terhadap stabilitas. Padahal, dalam demokrasi sejati, kritik bukan penghinaan, melainkan kontribusi.
Mengapa Kritik Membuat Telinga Panas? Secara psikologi, reaksi telinga panas terhadap kritik dijelaskan melalui konsep amygdala hijack yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence (1995). Ketika seseorang menerima masukan negatif, bagian emosional otaknya bereaksi cepat, memicu rasa tersinggung, marah, atau terhina, bahkan sebelum bagian rasional otak sempat memproses informasi tersebut secara objektif. Reaksi ini alamiah, tetapi harus dikendalikan jika kita ingin bertumbuh, baik secara personal maupun sebagai kelompok.
Di Indonesia, faktor budaya memperparah reaksi ini. Kita hidup dalam budaya malu (shame culture) di mana menjaga muka lebih penting daripada memperbaiki kesalahan. Kritik dipandang sebagai upaya mempermalukan, bukan sebagai ajakan untuk introspeksi.
Franz Magnis-Suseno, filsuf Indonesia, menulis: “Dalam budaya malu, yang lebih penting adalah mempertahankan kehormatan di mata orang lain, bukan mempertanggungjawabkan kebenaran.”
Karena itu, ketika dikritik, fokus kita bukan memperbaiki diri, melainkan membela diri mati-matian, bahkan dengan menyalahkan pihak lain. Ini berbahaya. Bangsa yang lebih takut malu daripada takut salah, akan berulang kali mengulangi kesalahannya.
Budaya Kritik dan Bangsa Besar. Kritik bukanlah musuh pembangunan; justru sebaliknya. Kritik adalah energi korektif yang menjaga bangsa tetap di jalur yang benar.
Dalam Development as Freedom (1999), Amartya Sen menegaskan bahwa “Hak untuk mengkritik adalah syarat mutlak bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa kritik, kekuasaan menjadi otoriter, birokrasi menjadi bebal, dan masyarakat kehilangan kepercayaan”.
Sejarah mencatat, bangsa-bangsa yang besar bukanlah bangsa yang steril dari kritik, tetapi bangsa yang mampu menumbuhkan kritik menjadi inovasi dan perbaikan. Lihatlah bagaimana negara-negara Skandinavia, Jepang pasca perang, atau bahkan Korea Selatan pasca reformasi, kritik yang bebas dan beradab adalah kunci transisi mereka menuju kemajuan.
Ketika ruang kritik dipersempit, maka yang tumbuh adalah bahasa tipu daya, bukan bahasa kebenaran. Melek Kritik, Jalan Menuju Kedewasaan Bangsa Bagaimana bangsa ini bisa maju jika masih alergi terhadap kritik?
Pertama, kita harus mendidik masyarakat untuk membedakan antara kritik dan serangan pribadi. Tidak semua ketidaknyamanan adalah penghinaan. Kritik yang valid harus dibedakan dari fitnah atau ujaran kebencian. Ini bisa diajarkan sejak dini, baik di sekolah maupun di keluarga.
Kedua, kita perlu menghormati hak untuk berbeda pendapat. Dalam demokrasi, perbedaan adalah kekayaan. Setiap kritik, sekeras apapun, harus diterima dalam kerangka mencari kebenaran, bukan sekadar mempertahankan gengsi.
Ketiga, kita harus membangun budaya permintaan maaf dan koreksi diri. Di negara-negara maju, pejabat publik yang melakukan kesalahan tidak segan-segan meminta maaf secara terbuka, dan memperbaiki diri. Di Indonesia, permintaan maaf sering dipandang sebagai kelemahan, padahal justru merupakan puncak kedewasaan moral. Suara minoritas, suara oposisi, bahkan suara rakyat biasa yang marah semuanya layak untuk didengar, bukan dibungkam.
Telinga Panas, Hati Terbuka. Mengkritik bukanlah kejahatan. Mengkritik adalah bentuk kecintaan terdalam pada bangsa ini. Mereka yang diam saat melihat kekeliruan justru berkhianat pada masa depan negeri ini.
Telinga boleh panas ketika mendengar kritik. Itu manusiawi. Tetapi setelah itu, akal sehat dan kebesaran hati harus mengambil alih. Kita harus bertanya, Apa pelajaran yang bisa saya ambil? Bagaimana saya bisa memperbaiki diri? Sebagaimana dikatakan Jurgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), “Kualitas demokrasi tidak diukur dari keseragaman pendapat, melainkan dari kualitas pertukaran argumentasi yang bebas.”
Bangsa besar adalah bangsa yang tidak hanya mampu berbicara, tetapi juga mampu mendengarkan, bahkan ketika yang terdengar adalah suara yang pedih. Indonesia yang besar bukanlah Indonesia yang membungkam kritik. Indonesia yang besar adalah Indonesia yang, meski telinganya panas, tetap memilih membuka hati untuk bertumbuh. Karena bangsa yang takut pada kritik, sesungguhnya takut pada dirinya sendiri. (Penulis adalah Pemimpin Redaksi Atalomba.com)