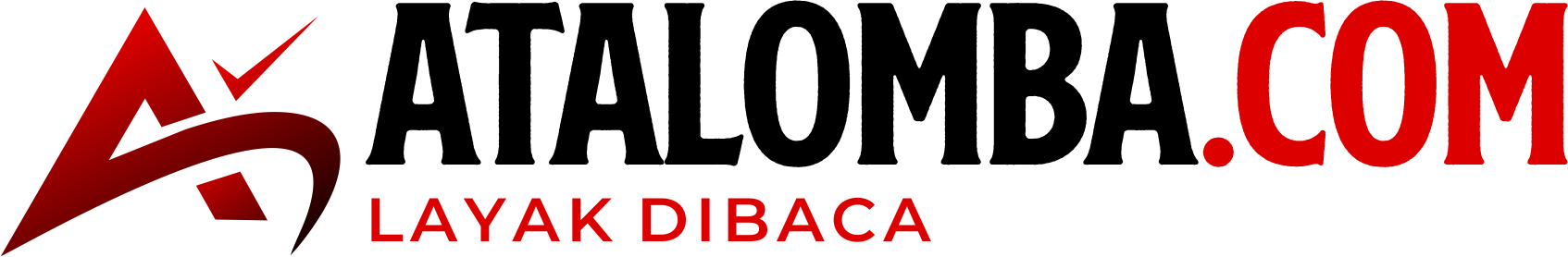SILANG SENGKARUT KONVERSI TANAH DI INDONESIA

Oleh: MIKAEL MALI, SE. SH. MH. CTL *
Setiap suku dan bangsa mengungkapkan kedekatan hubungan dengan tanah secara sangat takzim dan mengungkapkannya dengan berbagai cara. Dalam mitos dan filsafat yunani kuno tanah disebut Hades atau rumah peristirahatan terakhir bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Di Nusantara ini, beberapa daerah memiliki hubungan yang sangat sakral dan magis dengan tanah.
Suku Jawa menghargai tanah dengan sejumlah sebutan, seperti siti, bumi atau lemah. Suku Sunda menyebutnya tanawih, lumah. Suku bali memanggilnya palemahan. Suku Papua menghormati sebagai mama. Di suku Dayak, orang menyebutnya petak, bumi.
Tidak pernah dibayangkan, manusia hidup tanpa tanah. Hubungannya bersifat abadi. Tidak ada kehidupan tanpa tanah dan air. Tanah mempunyai hubungan yang sangat bermakna bagi manusia sesuai dengan ruang dan waktunya. Karena itu pula, manusia senantiasa menjaga keharmonisan hubungannya dengan tanah dan alam sekitarnya melalui berbagai tata laku atau ritus.
Pemahaman semacam itu terguncang ketika masyarakat Nusantara bertemu dengan bangsa-bangsa lain, yang membawa pemahaman tentang tanah yang berbeda dan memiliki hukum atau nilai yang berbeda. Dan itulah yang terjadi. Bangsa colonial Belanda datang ke Nusantara dengan membawa pemahaman bahwa tanah adalah benda tetap, yang disebut Terra, suatu konsep yang diadposi dari ahli pikir Romawi, dan membawa hukum pertanahan yang pada umumnya mengadopsi Hukum Romawi. Menurut pandangan hukum Romawi, tanah diklasifikasi sebagai benda dan digunakan bagi kepentingan militer dan pertanian.
Pertemuan itu menimbulkan masalah pada masa itu dan residunya masih tersisa hingga saat ini. Pada masa awal penjajahan, masalahnya adalah diambilnya tanah-tanah milik Masyarakat dan disewakan kepada orang-orang Eropah demi kepentingan penjajahan. Saat ini, masalahnya terletak pada konflik kepemilikan yang belum berhasil diuraikan yang disebabkan oleh berbagai hal.
Tulisan ini menyoroti sejarah pemberian berbagai hak kepada orang-orang Eropah untuk menguasai dan menggarap tanah di Hindia Belanda (kini: Indonesia). Sorotan ini penting untuk memberikan latar belakang tentang kasus-kasus agraria yang terkait dengan kepemilikan tanah-tanah, terutama di Jawa dan Sumatera, di mana pemerintah colonial banyak terbitkan pengalihan hak atas tanah kepada orang-orang Eropah atau Barat.
Motif Ekonomi dari Kolonialisme. Rempah-rempah dari Maluku sudah dikenal di Eropah pada abad 15 dan 16. Rute dagang yang membawa rempah-rempah itu ke Eropah dilakukan melalui Jalan Sutra, yang dijalankan oleh para pedagang Cina, India, Arab. Barang dagangan itu kemudian mendapatkan pembelinya di Venice, Italia dan Konstantinopel (kini, Istambul, Turki). Dari kedua kota itu, rampah-rempah, yaitu pala dan cengkeh mencapai para konsumennya di negara-negara Inggris, Portugis, Spanyol dan juga Belanda.
Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar dan mendapat keuntungan dari perdagangan, Belanda akhirnya menempuh jalur panjang ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Pada tahun 1596, empat kapal Belanda mendarat di Banten. Pada tahun 1602, mereka mendirikan satu armada dagang yang diberi nama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie).
Sejak itu, mulailah upaya untuk membentuk koloni mereka di Nusantara agar mereka menguasai perdagangan rempah-rempah secara monopolistis. Untuk mendukung monopoli itu, mereka membangun pasukan bersenjata. Tindakan-tindakan itu membuat mereka mampu mempengaruhi penguasa-penguasa lokal dan kemudian menempatkan penguasa lokal di bawah kekuasaan VOC.
Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat kedudukan koloni dan meningkatkan keuntungan ekonomi dari monopoli perdagangan. VOC menerima hak dari pemerintah di negeri Belanda untuk menjalankan kekuasaan yang berdaulat atas daerah yang dikuasai dengan kekuatan senjata.
Dengan kekuatan senjata dan monopoli perdagangan, VOC menganggap dirinya sebagai pemilik tanah dari daerah kekuasaannya. Organisasi dagang, yang lazim disebut Kompeni itu, memberikan tanah kepada bekas pegawai VOC, juga orang Belanda yang datang sebagai transmigran ke Nusantara. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar VOC mendapatkan biaya sewa dan pajak dari hasil tanah tersebut.
Hukum Agraria VOC. Tanggal 18 Agustus 1620, VOC mengeluarkan plakat atau maklumat peletakan dasar pertama pelaksanaan kadaster (pendaftaran tanah) dan penyelenggaraan pendaftaran hak di Hindia Belanda. Plakat itu juga menetapkan pendaftaran segala pekarangan dan pohon yang diberikan VOC dan pencatatan nama pemiliknya. Tanggal 23 Juli 1680, VOC mengeluarkan plakat yang mengatur susunan dan tugas Dewan Heemraden. Itu adalah satu lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan di luar kota Batavia (Jakarta), untuk melaksanakan tugas kadaster. Tugasnya adalah membuat peta umum tentang tanah di wilayah kerjanya. Pada setiap peta dicatat luas tanahnya serta nama pemiliknya.
Pasal 19 plakat tanggal 23 Juli 1680 menetapkan pula bahwa setiap orang tidak diperkenalkan menjual atau mengalihkan bidang tanahnya yang terletak di luar tembok kota, kecuali memberitahu terlebih dahulu kepada Dewan Heemraden. Dengan tujuan mencegah agar tidak terjadi lepas kontrol atas pemindahan bidang tanah. Heemradenkennis bertugas untuk melakukan kembali pengukuran tanah yang hendak dialihkan belum punya peta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Kebijakan politik Agraria yang sangat terkenal pada masa awal terbentuknya VOC dan menimbulkan masalah pertanahan yang berkepanjangan antara lain:
a. Contigenten
Pajak atas hasil tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial (kompeni). Kebijakan pajak tanah ini diperkenalkan pada tahun 1799. Sultan Hamengkubuwono II menerima politik pajak baru yang dikenal licik itu, Dengan ketentuan yang dikenal dengan sebutan Pancasan ini, petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa dibayar seperserpun. Kebijakan ini menimbulkan protes petani pengguna sawah atau ladang (kelompok sikep) karena kewajiban membayar pajak tanah. Keadaan sosial ekonomi yang memburuk pada masa itu menjadi pemicu protes para petani dan meletus perang di berbagai wilayah. Ini menjadi salah satu perang terbesar yang disebut Perang Jawa (Petani Jawa). Perang ini memakan korban jiwa baik dari rakyat maupun dari pihak Belanda.
b. Verplicthe leverante
Ini adalah satu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni bersama dengan para raja bahwa petani berkewajiban menyerahkan hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan sepihak.
c. Roerendiensten
Kebijakan ini dikenal dengan kerja rodi yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan.
Kebijakan Agraria Setelah VOC. Kebijakan agraria semacam itu terus berlanjut bahkan setelah perusahaan dagang VOC bubar pada tahun 1799 di mana kewenangan dan kewajiban VOC diambil alih oleh pemerintahan penjajahaan Belanda. Gubernur Jendral pertamanya, Herman Willem Daendles (1800-1811) menetapkan kebijakan. Dalam kebijakan itu, Willem Daendles menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah-tanah yang dijual itu dikenal dengan sebutan tanah patikelir.
Beralih ke penguasaan Inggris, Gubernur Thomas Stamford Rafless (1811-1816) menetapkan kebijakan landrent atau pajak tanah. Dalam ketentuan itu, kekuasaan tanah telah berpindah dari tanah milik raja (daerah swapraja di jawa) kepada pemerintah Inggris. Artinya, hak pemilikan atas tanah tersebut beralih kepada raja Inggris.Tanah yang dikuasai bukan miliknya, melainkan milik raja Inggris. Rakyat wajib membayar pajak tanah kepada raja Inggris.
Dalam mengatur kententuan LANDRENT ini, pemerintah kolonial tidak langsung berkontak dengan rakyat. Pelaksanaannya dijalankan oleh kepala desa. Kepala desa diberi kekuasaan untuk menetapkan besarnya sewa yang wajib dibayar oleh setiap petani. Kepala desa diberi kewenangan untuk mengadakan perubahan kepemilikan tanah tersebut kepada petani yang bersedia dan mampu membayar biaya sewa. Jadi, kepala desa memiliki kekuasaan yang besar, sebagai perpanjangan kekuasaan kolonial. Sewa tanah pertanian itu dibayar dengan cara bagi hasil panen. Bagi penggarap sawah, mereka harus menyerahkan setengah, dua perlima atau sepertiga hasil panen. Sedangkan penggarap tanah kering harus menyerahkan seperempat hingga setengah dari hasil panen.
Setelah berkuasa selama empat tahun, daerah Jawa diserahkan kembali kepada Belanda. Gubernur Jendral Johanes Van Den Bosch pada tahun 1830 menetapkan kebijakan pertanahan yang dikenal dengan sistem tanam paksa atau cultuur stesel. Dalam kebijakan ini, para petani dipaksa menanam satu jenis tanaman tertentu yang langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar Internasional. Hasil pertanian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaganya yaitu seperlima bagi masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu satu tahun.
Tahun berganti, kebijakan pun berubah. Pada tahun 1870 Belanda memberlakukan Agrarische Wet Stb. 1870 No.55. Dengan berlakunya ketentuan baru itu, politik monopoli (politik kolonial konservatif) dihapuskan dan digantikan dengan politik liberal. Pemerintah tidak ikut mencampuri di bidang usaha. Pengusaha diberikan kesempatan dan kebebasan mengembangkan usaha dan modalnya di bidang pertanian Indonesia.
Agrarische Wet merupakan hasil rancangan dari wet (undang-undang yang diajukan oleh menteri jajahan de waal). Agrarische Wet diundangkan dalam Stb.1870 No.55. Ketentuan ini menambahkan ayat-ayat baru untuk melengkapi pasal 62 Regering Reglement (RR) Stb.1854 No.2. RR itu terdiri dari atas 3 ayat dengan tambahan 5 ayat baru (ayat 4 sampai dengan ayat 8).
Pasal 62 RR kemudian mejadi pasal 51 Indische Staatsregeling (IS), Stb.1925 No. 447. Isi pasal 51 IS adalah sebagai berikut. Gubernur Jendral tidak boleh menjual tanah. Tanah yang dimaksukan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. Gubernur Jendral dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonasi.
Menurut ketentuan Ordonasi itu, seseorang bisa diberikan Hak Erfpacht untuk menguasai tanah selama tidak lebih dari 75 tahun. Gubernur Jendral menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi. Gubernur Jendral tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun temurun (hak milik adat) atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonasi.
Ketentuan lain tentang persewaan tanah diatur melalui Agrarische Besluit Stb.1870 No.118. Pasal 1 Agrarische Besluit memuat suatu pernyataan yang dikenal dengan Domein Verklaring (pernyataan kepemilikan), yang pada garis besarnya berisikan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah domein (milik) Negara. Atas dasar Domein Verklaring itu, tanah di Hindia Belanda dibagi dalam dua klasifikasi: Pertama adalah Vrijlands Domein atau tanah Negara bebas, yaitu tanah yang diatasnya tidak ada hak penduduk bumiputera. Kedua adalah Onvrijlands Domein atau tanah Negara tidak bebas, yaitu tanah yang diatasnya ada hak penduduk maupun desa.
Domein Verklaring ini memberikan dua manfaat. Pertama, Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht. Kedua, Untuk keperluan pembuktian, yaitu apabila negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan haknya.
Perkenalan hukum hak barat dalam mengatur tanah-tanah di Nusantara menyebabkan adanya berbagai hukum yang berlaku (dualisme hukum). Di samping hukum hak barat itu, pada saat yang sama berlaku juga hukum agraria adat, hukum agraria swapraja dan hukum agraria antar golongan. Hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria barat yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht. Hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria adat daerah masing-masing disebut tanah-tanah hak adat, misalnya tanah desa, tanah bengkok. Hukum hak atas tanah lain merupakan ciptaan pemerintah swapraja, misalnya Grant Sultan. Ini adalah semacam hak milik adat yang diberikan pemerintah swapraja khusus bagi kaula swapraja, dan didaftarkan dikantor swapraja.
Berbagai hukum agraria yang berlaku memberikan hak jaminan atas tanah bagi mereka yang menguasai tanah tersebut.
Beberapa hak jaminan atas tanah pada masa berlakunya hukum agraria kolonial, antara lain. Pertama, lembaga hypotheek diperuntukan bagi hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat, yaitu hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht. Lembaga crediet-verband diperuntukan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Lembaga jonggolan di Jawa, yang di Bali disebut makantah dan di Batak disebut tahan, dalam hubungannya dengan hutang piutang di kalangan masyarakat, di mana debitur menyerahkan tanahnya sebagai jaminan hutang kepada kreditur.
Dalam hal pendaftaran tanah, Berdasarkan Overschrijving ordonnantie Stb. 1834 No.27, pendaftaran dilakukan di kantor pendaftaran tanah atas tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan diberikan sertifikat kepada pemegang haknya sebagai tanda bukti. Sedangkan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah, sehingga tidak ada sertifikat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum.
Dengan demikian, tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam bidang hukum agraria bagi rakyat Indonesia asli. Alasannya, pertama, dari segi perangkat hukum, bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat, perangkat hukumnya tertulis yaitu diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan, bagi rakyat Indonesia asli berlaku hukum agraria adat, yang perangkat hukumnya tidak tertulis, yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan Masyarakat. itulah yang berlaku sebagai hukum. Kedua, dari segi pendaftaran, Untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, misalnya hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht dilakukan pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghasilkan tanda bukti yaitu sertifikat (Rechts Kadaster atau legal cadaster).
Sedangkan, untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum. (Fiscal Cadaster) Dari uraian di atas, jelas bahwa sistem hukum kolonial memperlihatkan wajah yang mendominasi, eksploitatif, diskriminatif dan dependen. Dampak dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda adalah tidak adanya kesatuan hukum atau terjadi dualisme hukum, yaitu sistem hukum barat dan hukum adat secara simultan. Pluralisme hukum adat dibiarkan berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik ekonomi penjajah.
Residu Kolonial dalam Urusan Konversi Hak Tanah
Setelah kemerdekaan, hukum agraria Belanda tidak berlaku lagi. Namun demikian, urusan kepemilikan tidak begitu saja selesai. Sebagian tanah jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak, yang menguasai secara fisik. Para pemegang hak tidak ditemukan. Hal-hal semacam itu menimbulkan komplikasi di lapangan.
Republik Indonesia baru mengundangkan hukum agrarianya pada tahun 1960, yang dikenal dengan UU Pembaruan Agraria. Undang-undang ini bertujuan untuk menertibkan administrasi pencatatan hak atas tanah. Setiap penguasa fisik satu bidang tanah harus memiliki data-data legal penguasaannya.
Namun, faktanya, banyak tanah di Jawa dan Sumatera, yang atasnya dulu diberlakukan hukum hak Barat, memiliki tumpang tindih klaim atau kepemilikan yang tidak disertai dengan bukti yang sah. Hal ini menunjukkan satu fakta bahwa konversi hak atas tanah bukanlah suatu urusan yang mudah atau semudah membalikkan telapak tangan.
Fakta ini menyebabkan tanah, yang diniatkan untuk memiliki fungsi ekonomi, tidak memberi manfaat yang optimal. Belum lagi fungsi ekonomi tersebut harus bersaing dengan fungsi-fungsi mendasar lainnya, seperti hak untuk memiliki hunian yang layak, walaupun di atas lahan yang bermasalah. Fakta ini merefleksikan sengkarut masalah tanah, warisan kolonial, yang tidak mudah diuraikan. Bisa, tetapi perlu niat baik dan usaha keras agar bisa memberi manfaat bagi banyak pihak terkait.***